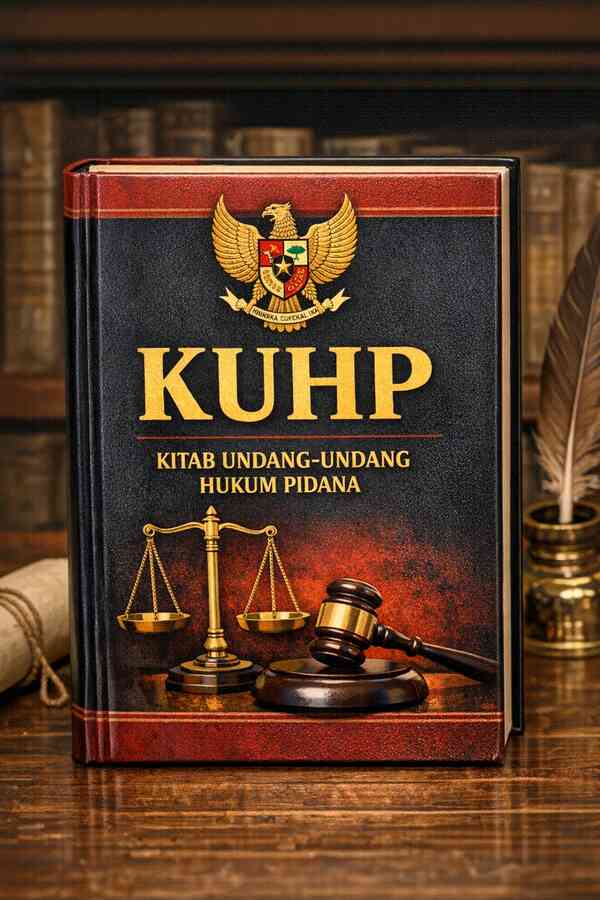portal kabar – Polisi perlu mengubah cara berpikirnya, terutama dalam menangani kasus kekerasan seksual. Seringkali, polisi tidak memahami bagaimana cara melindungi korban dalam kasus ini. Mereka kadang memilih keadilan restoratif, yaitu solusi yang seharusnya menguntungkan semua pihak, tetapi sering kali malah menyakiti korban lebih dalam.
Contohnya, dalam kasus pemerkosaan, ada polisi yang lebih memilih untuk menikahkan pelaku dengan korban sebagai solusi, yang jelas-jelas menguntungkan pelaku.
Satu kasus yang menarik perhatian adalah Bripda Fauzan (FA) dari Polda Sulawesi Selatan. Ia mendapat sanksi dipecat karena memperkosa mantan pacarnya, tetapi setelah mengajukan banding dan menikahi korban, ia kembali bertugas. Kasus ini terjadi pada tahun 2023.
Pada Desember 2023, sanksinya diubah menjadi demosi selama 15 tahun dan ia dipindah ke Polres Toraja Utara. Namun, setelah menikah, FA diduga menelantarkan istri yang juga merupakan korban pemerkosaan, dan tidak mau tinggal bersama. Pengacara korban menyatakan bahwa FA tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami.
Polda Sulsel mengakui bahwa keputusan banding telah mengubah sanksi FA, tetapi kini ia dilaporkan lagi karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkait penelantaran istri.
Masalahnya berasal dari penerimaan banding yang seharusnya tidak terjadi. Menikahi korban pemerkosaan seharusnya tidak menghentikan proses hukum. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menekankan pentingnya keadilan bagi korban.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan kasus ini menunjukkan bahwa polisi masih banyak melakukan kesalahan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pembatalan sanksi di sini menunjukkan adanya perlindungan bagi anggota polisi yang berbuat salah.
Isnur, dari YLBHI, juga menekankan bahwa menikahi korban pemerkosaan adalah hal yang salah. Korban tidak seharusnya dipaksa untuk menikahi pelaku karena itu hanya akan menambah trauma.
Menikahi korban pemerkosaan menjadi praktik yang sering terjadi dan kadang didukung oleh aparat dengan menyebutnya keadilan restoratif. Namun, UU TPKS melarang praktik ini dan mengancam pelaku dengan hukuman penjara.
Sementara itu, Kombes Zulhan dari Polda Sulsel menyatakan bahwa FA dianggap bertanggung jawab setelah menikahi korban. Namun, setelah laporan KDRT, mereka berencana untuk memanggil FA kembali.
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menganggap bahwa ada masalah dalam keputusan banding FA. Ia meminta Mabes Polri untuk mengevaluasi kasus ini dan memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang.
Ardi menyatakan bahwa Polri harus memperbaiki cara mereka menangani kasus kekerasan seksual dan meningkatkan pemahaman anggota tentang perlindungan hak-hak perempuan melalui pelatihan.
Kepercayaan publik terhadap Polri semakin menurun akibat kasus-kasus seperti ini. Laporan terakhir menunjukkan bahwa mayoritas interaksi di media sosial tentang Polri bersifat negatif.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menganggap keputusan banding FA menunjukkan celah hukum. Dia menekankan bahwa menikahi korban pemerkosaan sering kali digunakan sebagai cara untuk menghindari sanksi hukum.
Korban memiliki dua pilihan: melaporkan kembali FA atau meminta Propam untuk menyelidiki dugaan terbaru. Sugeng berharap langkah ini bisa membersihkan nama baik Polri.
Dewi Rahmawati Nur Aulia dari The Indonesian Institute menganggap tindakan Polri dalam kasus ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap kasus kekerasan seksual. Polri seharusnya menjadi pelindung dan penegak keadilan bagi korban.
Kultur patriarki dalam sistem penanganan Polri menjadi penghalang serius dalam menangani kasus kekerasan. Hal ini membuat Polri kehilangan kepercayaan publik yang sangat diperlukan.
Pemerintah perlu menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk meningkatkan penanganan kasus kekerasan seksual di Polri. Dengan cara ini, diharapkan aparat penegak hukum lebih siap menghadapi isu-isu kekerasan seksual.
pram/sumber Tirto